
Segala puji kepada Tuhan pencipta alam semesta!
Tulisan saya dibawah ini dipersiapkan dalam bentuk “draft” dan karena itu mengalami editing secara berangsur.
Salam dari Sunshine Coast, Queensland, Australia,
Andreas Nataatmadja

Segala puji kepada Tuhan pencipta alam semesta!
Tulisan saya dibawah ini dipersiapkan dalam bentuk “draft” dan karena itu mengalami editing secara berangsur.
Salam dari Sunshine Coast, Queensland, Australia,
Andreas Nataatmadja
“Jadi, kita seharusnya sudah lulus dari ajaran-ajaran dasar tentang Kristus. Kita perlu maju terus bukan mundur ke awal lagi. Kehidupan baru kita dimulai dengan berpaling dari kejahatan yang kita lakukan dan dengan percaya pada Allah. Itulah ketika kita diajar tentang baptisan, penumpangan tangan di atas orang-orang untuk memberkati mereka, kebangkitan dari kematian dan penghakiman akhir. Sekarang kita perlu maju dengan ajaran yang lebih dalam.” Ibrani 6:1–2

Belakangan ini, melalui berbagai media, orang melihat seorang pemimpin negara menerima penumpangan tangan dari tokoh-tokoh gereja sebelum memulai sebuah peperangan. Peristiwa itu menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang bertanya-tanya, ada yang merasa aneh, bahkan ada yang menertawakannya.
Bagi sebagian orang, tindakan menumpangkan tangan terlihat seperti ritual keagamaan yang tidak jelas maknanya. Namun bagi orang percaya, Alkitab menunjukkan bahwa tindakan sederhana ini memiliki makna rohani yang dalam.
Menariknya, penulis kitab Ibrani memasukkan penumpangan tangan sebagai salah satu ajaran dasar iman Kristen. Artinya, praktik ini sudah dikenal dan dipahami oleh gereja mula-mula sebagai bagian dari kehidupan rohani.
Di dalam Alkitab, penumpangan tangan adalah tindakan simbolis yang menggambarkan bahwa Allah sedang bekerja melalui umat-Nya. Bukan tangan manusia yang memberi kuasa, tetapi Tuhan yang bekerja melalui doa dan iman.
Dalam Perjanjian Lama kita melihat Musa menumpangkan tangan kepada Yosua ketika ia menyerahkan kepemimpinan Israel kepadanya. Melalui tindakan itu, bangsa Israel mengetahui bahwa Tuhan telah menetapkan Yosua untuk memimpin mereka.
Dalam Perjanjian Baru, Yesus menumpangkan tangan kepada anak-anak dan memberkati mereka. Di tengah dunia yang sering mengabaikan yang kecil dan lemah, Yesus menunjukkan bahwa setiap kehidupan berharga di hadapan Tuhan.
Para rasul kemudian melanjutkan praktik ini. Mereka menumpangkan tangan ketika mendoakan orang-orang percaya agar menerima Roh Kudus. Mereka juga menumpangkan tangan ketika mengutus orang-orang tertentu untuk pelayanan di dalam gereja.
Semua ini menunjukkan bahwa penumpangan tangan adalah tanda persekutuan, doa, dan penyerahan seseorang ke dalam pekerjaan Tuhan. Penumpangan tangan bukan tugas khusus yang Tuhan berikan kepada tokoh gereja, tetapi kepada semua orang percaya.
Namun Alkitab juga memberi peringatan penting. Rasul Paulus menasihati agar penumpangan tangan tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Tindakan ini bukan sekadar formalitas atau simbol yang kosong. Ada tanggung jawab rohani di dalamnya.
Penumpangan tangan tidak boleh dijadikan “show” dan tidak boleh dipermainkan karena adanya hubungan dengan kebesaran, kesucian, dan kedaulatan Tuhan. Ini bukan sekadar kebiasaan atau tindakan yang tidak berarti, yang bisa dipermainkan.
Karena itu, tujuan penumpangan tangan yang benar bukanlah untuk memuliakan manusia, memberi legitimasi pada ambisi pribadi, atau menjanjikan keberhasilan duniawi. Semua tindakan itu seharusnya mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sumber segala kuasa dan berkat.
Pada akhirnya, penumpangan tangan mengingatkan kita akan satu hal sederhana tetapi mendalam: Tuhan bekerja melalui umat-Nya. Melalui doa yang tulus, melalui pelayanan yang setia, dan bahkan melalui sentuhan yang penuh kasih, Tuhan dapat menyatakan anugerah-Nya kepada dunia.
Kiranya setiap kali kita melihat atau mengalami penumpangan tangan, kita diingatkan bahwa kehidupan iman bukan sekadar kata-kata, tetapi juga tindakan kasih, doa, dan penyerahan diri kepada Tuhan.
Doa Penutup
Tuhan yang penuh kasih, ajar kami memahami setiap tindakan iman dengan hati yang benar. Biarlah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu untuk membawa berkat, penguatan, dan kasih bagi sesama. Pakailah kami untuk memuliakan nama-Mu dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28

Setiap hari kita membaca berita yang membuat hati gelisah. Perang terjadi di berbagai tempat. Ketegangan politik meningkat. Ekonomi dunia terasa tidak stabil. Harga minyak naik, ketidakpastian bertambah, dan masa depan terasa kabur. Banyak orang bertanya dalam hati: Apakah dunia ini sedang lepas dari kendali? Bahkan sebagian orang percaya pun kadang diam-diam bergumul dengan pertanyaan yang sama: Apakah Tuhan masih memegang kontrol atas sejarah manusia?
Pertanyaan ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak zaman Alkitab, umat Tuhan juga hidup di tengah dunia yang kacau. Bangsa Israel pernah mengalami penjajahan, pembuangan, perang, dan penindasan. Namun di tengah semua itu, firman Tuhan terus mengingatkan bahwa sejarah manusia tidak berjalan secara acak. Ada tangan ilahi yang memimpin semuanya.
Rasul Paulus menulis sebuah kalimat yang sangat kuat dalam Roma 8:28. Ia berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan “dalam beberapa hal” atau “dalam hal-hal yang baik saja.” Ia mengatakan dalam segala sesuatu. Artinya, bahkan dalam kekacauan, penderitaan, dan ketidakpastian sekalipun, Tuhan tetap bekerja untuk kebaikan umat-Nya.
Alkitab menunjukkan bahwa tidak ada satu peristiwa pun di dunia ini yang berada di luar pengetahuan dan pemeliharaan Tuhan. Dari jatuhnya sehelai rambut hingga naik turunnya kerajaan-kerajaan besar, semuanya berada di dalam pengawasan-Nya. Sejarah, termasuk apa yang terjadi antara Israel dan Iran, bukanlah kumpulan kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang besar yang sudah ditulis dalam Alkitab.
Namun di sisi lain, Alkitab juga mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral atas tindakannya. Perang, kejahatan, penindasan, dan ketidakadilan sering kali lahir dari keputusan manusia yang berdosa. Tuhan tidak menciptakan kejahatan itu. Tetapi dalam misteri kedaulatan-Nya, Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi.
Inilah yang sering disebut sebagai kehendak permisif Tuhan. Ada hal-hal yang memang dikehendaki Tuhan secara langsung, tetapi ada juga hal-hal yang Dia izinkan terjadi demi tujuan yang lebih besar yang sering kali belum kita pahami.
Contoh yang paling jelas adalah salib Kristus. Penyaliban Yesus adalah kejahatan manusia yang luar biasa. Namun justru melalui peristiwa itu, Tuhan membawa keselamatan bagi dunia. Apa yang tampak sebagai kekalahan ternyata menjadi kemenangan terbesar dalam sejarah.
Karena itu, ketika kita melihat dunia yang kacau, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia mungkin mengizinkan dunia melewati masa-masa gelap, tetapi itu tidak berarti Dia meninggalkan ciptaan-Nya.
Bagi orang percaya, kebenaran ini menjadi sumber penghiburan yang dalam. Kita mungkin tidak memahami semua yang terjadi. Kita mungkin tidak bisa menjelaskan mengapa penderitaan datang. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sedang menulis cerita yang lebih besar daripada yang bisa kita lihat saat ini.
Dunia mungkin terlihat kacau. Berita mungkin penuh kecemasan. Tetapi satu hal tidak berubah: Tuhan masih memegang kontrol.
Suatu hari nanti, Tuhan akan menyatakan keadilan-Nya sepenuhnya. Segala penderitaan akan berakhir. Kejahatan tidak akan menang selamanya. Allah akan memulihkan segala sesuatu menurut rencana-Nya yang sempurna.
“Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi.” Wahyu 21:4
Sementara kita masih hidup di dunia yang tidak sempurna ini, panggilan kita adalah tetap percaya, tetap setia, dan tetap berharap kepada Tuhan yang memegang sejarah.
Inilah pengharapan terakhir orang percaya: sejarah tidak berakhir dalam kekacauan, tetapi dalam pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Dan itu cukup untuk memberi kita damai di tengah badai.
Doa Penutup
Tuhan yang berdaulat,
Ketika kami melihat dunia yang penuh ketidakpastian, hati kami sering diliputi kekhawatiran. Perang, kejahatan, dan penderitaan membuat kami bertanya-tanya tentang masa depan.
Namun hari ini kami diingatkan bahwa Engkau tidak pernah kehilangan kendali. Engkau adalah Tuhan yang memegang sejarah, Tuhan yang bekerja bahkan melalui keadaan yang tidak kami mengerti.
Tolonglah kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Berikan kami hati yang tenang di tengah kekacauan dunia. Ajarlah kami untuk hidup setia, mengasihi sesama, dan berharap kepada rencana-Mu yang sempurna.
Di dalam tangan-Mu kami menyerahkan hidup kami dan masa depan dunia ini.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
“Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci; ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai.” Pengkhotbah 3:8

Ketika kita membaca ayat ini, kita mungkin merasa sedikit terganggu. Mengapa Alkitab menyebut bahwa ada “waktu untuk perang”? Bukankah iman seharusnya selalu berbicara tentang damai?
Namun kitab Kitab Pengkhotbah bukanlah kitab yang penuh slogan rohani yang indah. Kitab ini justru sangat jujur melihat kehidupan manusia. Penulisnya mengamati dunia sebagaimana adanya—dunia yang indah tetapi juga rusak, dunia yang penuh sukacita tetapi juga penuh konflik.
Di dalam pasal 3, Pengkhotbah menyebutkan berbagai pasangan pengalaman hidup: lahir dan mati, menanam dan mencabut, menangis dan tertawa. Semua itu menunjukkan bahwa hidup manusia bergerak dalam berbagai musim yang tidak selalu kita kendalikan. Demikian juga dengan perang dan damai.
Sepanjang sejarah manusia, perang selalu muncul. Dari konflik kecil sampai peperangan besar antarbangsa. Bahkan sejak awal sejarah Alkitab, kekerasan sudah muncul ketika Kain membunuh saudaranya Habel dalam Kitab Kejadian 4. Sejak saat itu, dosa di dalam hati manusia terus melahirkan permusuhan, iri hati, dan kekerasan.
Ayat dalam Kitab Pengkhotbah 3:8 bukanlah perintah untuk berperang. Ayat ini adalah pengakuan realistis tentang dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam dunia seperti ini, konflik tidak bisa dihindari sepenuhnya.
Tetapi Alkitab tidak berhenti pada realitas itu.
Para nabi Perjanjian Lama justru melihat ke depan kepada suatu masa ketika perang tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nabi Yesaya menggambarkan suatu masa ketika pedang ditempa menjadi mata bajak dan tombak menjadi pisau pemangkas. Itu adalah gambaran dunia yang dipulihkan oleh Tuhan.
Penggenapan arah itu terlihat dalam ajaran Yesus Kristus. Ia berkata, “Berbahagialah orang yang membawa damai.” Ia bahkan mengajarkan untuk mengasihi musuh. Ini adalah standar yang jauh lebih tinggi daripada sekadar menghindari perang.
Namun Yesus Kristus juga tidak menutup mata terhadap kenyataan dunia. Ia berkata bahwa manusia akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Artinya, selama dunia masih berada di bawah bayang-bayang dosa, konflik kemungkinan akan terus muncul. Di sinilah orang percaya dipanggil untuk memiliki sikap hati yang berbeda.
Kita tidak boleh memuliakan perang. Kita juga tidak boleh membenci manusia yang berada di pihak lain. Perang mungkin terjadi dalam sejarah, tetapi kebencian tidak boleh menguasai hati kita.
Sebaliknya, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di mana pun kita berada—di keluarga, di gereja, di masyarakat, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Dunia mungkin tidak selalu bisa menghindari konflik, tetapi hati orang percaya tetap dipanggil untuk mengejar damai.
Ayat dalam Kitab Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa sejarah manusia bergerak melalui berbagai musim. Ada masa sulit, ada masa gelap, bahkan ada masa perang. Tetapi semua itu tidak berada di luar pengetahuan Tuhan.
Pada akhirnya, sejarah tidak ditentukan oleh peperangan manusia, melainkan oleh rencana Allah yang jauh lebih besar. Dan rencana itu bergerak menuju pemulihan, menuju damai yang sejati.
Hal terpenting yang dapat kita lakukan di masa perang adalah berdoa untuk kebijaksanaan yang saleh bagi para pemimpin kita, berdoa untuk keselamatan militer kita, berdoa untuk resolusi cepat untuk konflik, dan berdoa untuk korban minimum di antara warga sipil di kedua belah pihak.
Sementara kita masih hidup di dunia ini, kita menantikan hari ketika damai Tuhan akan menjadi kenyataan penuh bagi seluruh ciptaan.
Doa Penutup
Tuhan yang berdaulat atas sejarah,
Engkau melihat dunia yang sering dipenuhi konflik dan pertentangan. Ampuni kami ketika hati kami juga mudah dipenuhi kemarahan dan kebencian.
Ajarlah kami untuk menjadi pembawa damai di mana pun Engkau menempatkan kami. Berikan kami kerendahan hati untuk tidak cepat menghakimi, dan kasih untuk tetap melihat sesama manusia sebagai ciptaan-Mu.
Di tengah dunia yang sering bergolak, tuntunlah kami untuk tetap berharap kepada rencana-Mu yang lebih besar. Kami percaya bahwa pada akhirnya Engkaulah yang akan membawa damai yang sejati bagi dunia ini.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Amin.
“Tidak ada satupun dari segala janji baik yang diucapkan TUHAN kepada kaum Israel yang tidak dipenuhi-Nya; semuanya terpenuhi.” Yosua 21:45

Ada kalanya kita membaca Alkitab dengan jarak sejarah yang jauh. Nama-nama tempat dan bangsa terasa seperti cerita masa lampau. Tetapi ketika kita membuka berita dunia modern dan melihat nama Israel muncul hampir setiap hari, kita menyadari bahwa bangsa yang sering kita baca dalam Alkitab itu masih menjadi bagian dari percakapan dunia sampai sekarang.
Bagi sebagian orang Kristen, Israel modern dilihat sebagai pusat dari seluruh rencana Allah. Apa pun yang dilakukan negara itu dianggap benar, karena mereka adalah “bangsa pilihan”. Di sisi lain, ada juga yang bereaksi sebaliknya.
Karena konflik politik dan perang yang tidak kunjung berhenti, ada orang Kristen yang mulai menolak bahkan membenci Israel, seolah-olah bangsa itu tidak lagi memiliki tempat khusus dalam sejarah iman. Namun Alkitab mengajak kita melihat dengan cara yang lebih tenang dan lebih dalam.
Kitab Yosua mencatat sebuah kalimat yang sangat kuat: “Tidak ada satupun dari segala janji baik yang diucapkan TUHAN kepada kaum Israel yang tidak dipenuhi-Nya.” Kalimat ini adalah pengakuan bahwa Allah setia. Ia menepati janji-Nya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tanah yang dijanjikan diberikan, bangsa itu terbentuk, dan mereka mengalami pemeliharaan Tuhan dalam sejarah.
Dari bangsa inilah lahir begitu banyak hal yang membentuk iman kita. Melalui Israel, Allah memberikan wahyu-Nya kepada dunia. Hukum Taurat diberikan kepada mereka. Para nabi muncul dari tengah bangsa itu untuk menyatakan kehendak Tuhan. Dan yang paling penting, dari bangsa itulah lahir Mesias yang dijanjikan—Yesus Kristus, Juruselamat dunia.
Karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa Israel hanyalah bangsa biasa dalam Alkitab. Mereka memiliki peranan unik dalam sejarah keselamatan. Rasul Paulus bahkan berkata bahwa kepada merekalah dipercayakan perjanjian-perjanjian, ibadah, dan janji-janji Allah. Namun di sinilah kita perlu berhati-hati.
Alkitab tidak pernah berhenti pada bangsa atau tanah sebagai tujuan akhir.
Semua janji Allah kepada Israel sebenarnya menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Tanah perjanjian adalah bayangan dari kerajaan Allah yang lebih luas. Bait Allah menunjuk kepada kehadiran Allah yang sempurna. Dan seluruh hukum Taurat menemukan penggenapannya di dalam Kristus.
Puncak dari semua janji Allah bukanlah negara atau wilayah geografis tertentu, melainkan pribadi Yesus Kristus dan karya keselamatan-Nya bagi semua bangsa.
Di dalam Kristus, batas-batas etnis dan nasional mulai terbuka. Injil tidak lagi hanya bergerak di dalam satu bangsa, tetapi menjangkau seluruh dunia. Orang Yahudi dan bukan Yahudi dipanggil untuk datang kepada Tuhan yang sama.
Karena itu, sikap orang percaya terhadap Israel pada zaman sekarang seharusnya penuh keseimbangan.
Kita tidak boleh mengultuskan Israel modern seolah-olah negara itu selalu benar dalam segala hal. Negara mana pun di dunia tetap terdiri dari manusia berdosa, termasuk Israel. Kebijakan politik, perang, dan keputusan nasional tidak otomatis memiliki otoritas ilahi.
Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh membenci atau menolak keunikan Israel dalam sejarah penebusan manusia seperti yang dilakukan oleh mereka yang kurang memahami Alkitab. Melalui bangsa Israel Allah memilih untuk menyatakan diri-Nya dalam sejarah manusia. Mengabaikan peranan itu berarti kita juga melupakan bagaimana Allah bekerja dalam perjalanan keselamatan.
Sikap yang paling bijaksana adalah sikap yang penuh kerendahan hati. Kita mengakui kesetiaan Tuhan kepada Israel dalam sejarah. Kita bersyukur karena melalui bangsa itu Mesias datang ke dunia. Saat ini, kita tidak sepenuhnya tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi pada saat yang sama kita mengarahkan iman kita kepada Kristus, yang adalah pusat dari seluruh rencana Allah.
Pada akhirnya, harapan orang percaya tidak terletak pada kebangkitan satu bangsa, melainkan pada kerajaan Allah yang kekal. Kerajaan itu sedang dibangun oleh Kristus melalui Injil yang menjangkau segala suku, bahasa, dan bangsa.
Di situlah kita semua dipanggil untuk berdiri—bukan sebagai pengagung atau pembenci bangsa tertentu, tetapi sebagai umat yang memandang kepada Tuhan yang setia menepati janji-Nya.
Doa Penutup
Tuhan yang setia, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal menepati janji-Mu. Apa yang Engkau janjikan kepada umat-Mu dalam sejarah telah Engkau genapi dengan sempurna.
Kami bersyukur karena melalui bangsa Israel Engkau menyatakan firman-Mu, hukum-Mu, dan para nabi-Mu kepada dunia. Lebih dari itu, kami bersyukur karena melalui mereka Engkau menghadirkan Yesus Kristus, Juruselamat kami.
Tolong kami agar memiliki hati yang bijaksana dan rendah hati. Jauhkan kami dari sikap yang mengultuskan manusia atau bangsa mana pun. Tetapi juga jauhkan kami dari kebencian dan penghakiman yang tidak benar.
Ajar kami untuk melihat sejarah dengan mata iman, bahwa Engkau tetap bekerja dalam segala sesuatu menurut rencana-Mu yang besar. Teguhkan hati kami untuk selalu memandang kepada Kristus sebagai pusat pengharapan kami.
Biarlah hidup kami dipakai untuk menyatakan kasih dan keselamatan-Mu kepada semua orang, dari segala bangsa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
“tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.” Kitab Kejadian 2:17

Sejak dahulu manusia sering bertanya: jika Tuhan mengetahui segala sesuatu, mengapa Ia tidak menghentikan kejahatan sebelum terjadi?
Sebagian orang melihat perang, kekerasan, dan penderitaan di dunia lalu menyimpulkan bahwa Tuhan tidak ada. Ada pula yang berkata bahwa jika Tuhan ada, Ia tampaknya tidak memiliki tanggung jawab moral karena membiarkan begitu banyak kejahatan dan penderitaan terjadi di dunia.
Namun Alkitab justru memulai ceritanya dengan sesuatu yang sangat jelas: Tuhan sudah memberikan hukum moral kepada manusia sejak awal. Ia adalah pencipta moral, yang menuntun manusia dalam membedakan apa yang baik dan apa yang buruk.
Di taman Eden, Tuhan memberi perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah itu sederhana, tetapi sangat mendasar.
Melalui perintah itu Tuhan menunjukkan bahwa kehidupan manusia berada di bawah hukum moral yang berasal dari-Nya. Tuhan adalah sumber dari standar benar dan salah.
Ketika manusia melanggar perintah itu, konsekuensinya pun terjadi. Kematian masuk ke dalam dunia. Relasi manusia dengan Tuhan rusak, dan sejak saat itu dosa mulai bekerja di dalam hati manusia.
Kita melihat akibatnya tidak lama kemudian dalam kisah pembunuhan pertama di dunia. Kain membunuh adiknya, Habel. Iri hati dan kemarahan yang tidak dikendalikan berubah menjadi kekerasan.
Di sinilah banyak orang bertanya: jika Tuhan tahu apa yang akan terjadi, mengapa Ia tidak menghentikan Kain?
Pertanyaan itu sebenarnya mengandung asumsi bahwa Tuhan seharusnya membatalkan hukum-Nya setiap kali manusia melanggarnya. Tetapi jika Tuhan selalu mencegah konsekuensi dari dosa manusia, maka hukum moral yang Ia berikan tidak lagi memiliki arti.
Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai mesin yang otomatis melakukan kebaikan. Ia memberikan kemampuan untuk memilih. Karena itu manusia juga memikul tanggung jawab atas pilihannya.
Kain telah diperingatkan bahwa dosa sedang mengintip di depan pintu dan ia harus menguasainya. Tetapi ia memilih jalan yang lain dan karena itu harus menerima akibatnya. Namun kisah Alkitab tidak berhenti pada hukuman saja.
Setelah Kain melakukan pembunuhan, Tuhan memang menjatuhkan hukuman kepadanya. Ia menjadi pengembara di bumi. Ini menunjukkan bahwa dosa tidak pernah tanpa konsekuensi. Tetapi pada saat yang sama Tuhan juga menunjukkan kemurahan-Nya. Ia memberikan tanda perlindungan kepada Kain supaya orang lain tidak membunuhnya.
Di sini kita melihat dua hal yang berjalan bersama: keadilan dan kasih. Tuhan tidak membatalkan hukum-Nya, tetapi Ia juga tidak berhenti menyatakan belas kasihan.
Sejak awal sejarah manusia, Tuhan telah menunjukkan pola ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menghapus konsekuensi dari pelanggaran itu. Tetapi Ia mulai menyingkapkan rencana penebusan-Nya.
Rencana itu akhirnya mencapai puncaknya melalui Yesus Kristus. Di dalam Dia, kasih dan keadilan Allah bertemu secara sempurna. Dosa tidak diabaikan, tetapi dihukum. Namun manusia berdosa tetap diberi kesempatan untuk menerima pengampunan.
Ketika kita melihat dunia yang penuh konflik dan kekerasan, kita mungkin tergoda untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi Alkitab mengingatkan kita bahwa akar dari banyak kejahatan berada di dalam hati manusia sendiri—hati yang telah menjauh dari hukum Tuhan.
Namun kabar baiknya adalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan dunia ini. Ia tetap bekerja di dalam sejarah, memanggil manusia yang sesat untuk kembali kepada-Nya, dan menawarkan kehidupan yang baru melalui anugerah-Nya.
Karena itu, pertanyaan yang paling penting pagi ini bukanlah mengapa Tuhan tidak menghentikan kejahatan, seperti perang yang saat ini terjadi di Timur Tengah, tetapi apakah sesudah merasakan akibat dosa, seluruh umat manusia mau kembali kepada-Nya dan hidup menurut hukum serta kasih-Nya.
Doa Penutup
Tuhan yang Mahakudus,
Engkau telah memberikan hukum-Mu kepada manusia sejak awal. Engkau menunjukkan kepada kami jalan kehidupan, tetapi sering kali kami memilih jalan kami sendiri.
Ampunilah dosa kami ketika kami melanggar kehendak-Mu dan kemudian menyalahkan keadaan di sekitar kami. Ajarlah kami untuk hidup dengan hati yang taat kepada firman-Mu.
Terima kasih karena Engkau bukan hanya Allah yang adil, tetapi juga Allah yang penuh kasih. Terima kasih untuk anugerah penebusan yang Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus.
Tolonglah kami agar setiap hari belajar menguasai dosa yang mengintip di depan pintu hati kami, dan berjalan dalam terang-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
“Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya; maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram.” Kejadian 4:4–5

Ketika kita mendengar tentang perang—baik perang antarbangsa, konflik antar suku, atau bahkan pertengkaran antar manusia—kita sering mencari penyebabnya pada hal-hal yang kelihatan: wilayah, kekuasaan, sumber daya, atau ideologi. Sejarah manusia penuh dengan penjelasan semacam itu.
Namun Alkitab membawa kita jauh lebih dalam. Jika kita ingin memahami mengapa manusia berperang, kita tidak perlu mulai dari medan perang. Kita harus mulai dari sebuah ladang sederhana di awal sejarah manusia, ketika dua saudara mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di sanalah kita menemukan kisah Kain dan Habel.
Keduanya datang kepada Tuhan. Habel mempersembahkan anak sulung dari kawanan dombanya, sedangkan Kain membawa hasil tanahnya. Tetapi Alkitab mencatat sesuatu yang mengubah segalanya: Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya, tetapi tidak mengindahkan Kain dan persembahannya.
Reaksi Kain tidak langsung berupa kekerasan. Alkitab mencatat sesuatu yang lebih halus namun sangat berbahaya: “hati Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram.”
Perang pertama dalam sejarah manusia sebenarnya dimulai di dalam hati.
Kain merasa dirinya tersisih. Ia merasa posisinya di hadapan Tuhan terganggu. Habel, yang diterima Tuhan, tiba-tiba menjadi cermin yang menyakitkan bagi Kain. Bukannya memeriksa dirinya sendiri, Kain mulai memandang saudaranya sebagai ancaman. Padahal Habel tidak mengambil apa pun dari Kain.
Namun dalam hati yang sudah diliputi iri dan marah, kehadiran orang lain bisa terasa seperti ancaman terhadap keberadaan kita sendiri. Kain mulai melihat dunia seolah-olah hanya ada satu tempat penerimaan di hadapan Tuhan—dan Habel telah mengambilnya. Di sinilah akar dari hampir semua konflik manusia.
Manusia sering merasa bahwa keberadaan orang lain mengurangi keberadaannya sendiri. Keberhasilan orang lain terasa seperti kegagalan kita. Pengakuan yang diberikan kepada orang lain terasa seperti penolakan terhadap kita.
Dari sanalah lahir iri hati.
Dan dari iri hati lahir kebencian.
Dan dari kebencian lahir kekerasan.
Kain akhirnya mengajak Habel ke padang dan membunuhnya. Tidak ada tentara. Tidak ada senjata perang. Tidak ada strategi militer. Tetapi di situlah terjadi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia.
Dengan kata lain, perang pertama terjadi karena hati yang rusak.
Apa yang kita lihat hari ini dalam perang antarbangsa sebenarnya hanyalah versi besar dari tragedi yang sama. Negara merasa terancam oleh negara lain. Kelompok merasa posisinya terancam oleh kelompok lain. Pemimpin merasa kekuasaannya terancam oleh lawan-lawan mereka.
Ketika rasa takut dan keserakahan bertemu, manusia mulai percaya bahwa satu-satunya cara mempertahankan keberadaannya adalah dengan menyingkirkan orang lain.
Namun kisah Kain juga mengungkap sesuatu yang sangat penting: Tuhan sebenarnya memberi kesempatan kepada Kain untuk berhenti. Tuhan berkata kepadanya bahwa dosa sedang mengintip di depan pintu, tetapi Kain masih bisa menguasainya.
Sayangnya, Kain tidak memilih jalan itu. Ia memilih membiarkan dosa menguasai hatinya. Itulah sebabnya, dari sudut pandang iman, semua perang pada dasarnya adalah jahat. Bukan karena setiap orang yang terlibat di dalamnya jahat secara pribadi, tetapi karena perang adalah buah dari hati manusia yang sudah jatuh dalam dosa.
Perang mungkin dibungkus dengan kata-kata yang mulia: keamanan, kehormatan, keadilan, atau kemerdekaan. Tetapi jauh di dalam, akar terdalamnya sering kali tetap sama—ketakutan, iri hati, keserakahan, dan keinginan untuk menegaskan diri dengan mengorbankan orang lain.
Alkitab mengingatkan kita bahwa masalah terbesar manusia bukanlah sistem politik, ekonomi, atau militer. Masalah terbesar manusia adalah hati. Selama hati manusia tidak dipulihkan oleh Tuhan, konflik akan selalu muncul dalam berbagai bentuk; antar negara, antar suku, antar agama, antar gereja, dan juga antara suami dan istri.
Karena itu, panggilan orang percaya bukan hanya menolak kekerasan di luar, tetapi juga memeriksa hati sendiri. Sebab benih yang sama yang ada dalam diri Kain bisa juga tersembunyi dalam diri kita: iri ketika orang lain diberkati, marah ketika kita tidak dihargai, atau ingin menjatuhkan orang lain agar kita terlihat lebih baik.
Perdamaian sejati tidak dimulai di meja perundingan atau di panggung politik.
Perdamaian sejati dimulai ketika hati manusia dipulihkan di hadapan Tuhan.
Doa Penutup
Ya Tuhan,
Engkau yang melihat hati manusia lebih dalam daripada siapa pun.
Kami mengakui bahwa dunia ini penuh dengan konflik, kebencian, dan peperangan. Tetapi kami juga mengakui bahwa akar dari semua itu tidak hanya ada di luar diri kami, melainkan juga di dalam hati kami sendiri.
Ampuni kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk hidup rendah hati di hadapan-Mu. Berikan kepada kami hati yang bersyukur ketika orang lain diberkati, dan hati yang rela diperbaiki ketika Engkau menegur kami.
Di dalam nama Tuhan kami berdoa.
Amin.
“dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan Allah: Pada hari Aku memilih Israel, Aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir; Aku bersumpah kepada mereka: Akulah Tuhan Allahmu!” Yehezkiel 20:5

Istilah “bangsa pilihan” sering menjadi bahan ejekan bagi sebagian orang. Ada yang bertanya dengan nada sinis: jika Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, mengapa sejarah mereka penuh penderitaan, penganiayaan, perang, dan bahkan tragedi besar?
Pertanyaan seperti ini sebenarnya muncul karena banyak orang salah memahami arti kata “pilihan” dalam Alkitab. Mereka mengira bahwa bangsa pilihan berarti bangsa yang otomatis lebih mulia, lebih diberkati, atau pasti diselamatkan oleh Tuhan. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian.
Ayat dalam kitab nabi Yehezkiel memberi petunjuk penting tentang makna pilihan itu. Tuhan berkata, “Pada hari Aku memilih Israel… Aku menyatakan diri kepada mereka.” Kalimat ini menunjukkan bahwa pilihan Allah atas Israel berkaitan dengan penyataan diri-Nya dalam sejarah.
Dengan kata lain, Israel dipilih untuk menjadi bangsa yang mengenal Allah dan menerima wahyu-Nya. Melalui bangsa ini, Tuhan menyatakan hukum-Nya, memanggil para nabi, dan memperkenalkan diri-Nya kepada dunia sebagai Allah yang hidup.
Pilihan itu bukan sekadar kehormatan. Ia adalah panggilan dan tanggung jawab.
Sejarah Alkitab justru memperlihatkan bahwa bangsa Israel sering gagal menjalankan panggilan tersebut. Para nabi berkali-kali menegur mereka karena penyembahan berhala, ketidakadilan, dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Teguran keras datang dari nabi-nabi seperti Yesaya dan Yeremia.
Bahkan bangsa itu pernah mengalami kehancuran dan pembuangan sebagai akibat dari ketidaktaatan mereka. Semua ini menunjukkan bahwa menjadi bangsa pilihan tidak berarti kebal dari penghakiman Tuhan.
Lalu untuk apa sebenarnya Israel dipilih?
Dalam iman Kristen, pilihan itu memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar sejarah satu bangsa. Israel dipilih untuk menjadi saluran rencana keselamatan Allah bagi dunia.
Melalui sejarah bangsa ini, janji-janji Tuhan dipelihara dan nubuat-nubuat disampaikan. Dari garis keturunan mereka akhirnya lahir Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus.
Rasul Paulus menjelaskan bahwa kepada Israel dipercayakan banyak hal: perjanjian, hukum Taurat, ibadah kepada Allah, dan janji-janji-Nya. Namun ia juga menegaskan bahwa semua itu tidak otomatis membuat seseorang diselamatkan.
Keselamatan tidak pernah ditentukan oleh bangsa atau keturunan.
Dalam Perjanjian Baru, keselamatan dinyatakan terbuka bagi semua orang. Baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi dapat menjadi bagian dari umat Allah melalui iman kepada Kristus. Dengan demikian, tujuan akhir dari sejarah Israel bukanlah meninggikan satu bangsa di atas bangsa lain, melainkan membuka jalan keselamatan bagi seluruh dunia.
Jika kita melihat sejarah dengan jujur, menjadi “bangsa pilihan” justru sering berarti memikul penderitaan yang berat. Orang Yahudi mengalami pengusiran, penindasan, dan tragedi besar seperti Holocaust.
Hal ini menunjukkan bahwa pilihan Allah tidak selalu berarti kemudahan hidup di dunia. Sering kali pilihan itu berarti menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar daripada kepentingan satu generasi.
Karena itu, konsep “bangsa pilihan” dalam Alkitab sebenarnya bukanlah cerita tentang keistimewaan suatu bangsa. Ini adalah cerita tentang bagaimana melalui kasih-Nya Tuhan bekerja melalui sejarah manusia untuk menyatakan diri-Nya dan membawa keselamatan bagi seisi dunia.
Dan pada akhirnya, pusat dari seluruh kisah itu bukan Israel, melainkan Kristus—yang datang bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi bagi semua orang yang percaya kepada-Nya.
Doa Penutup
Tuhan yang Mahabijaksana,
Engkau adalah Tuhan atas segala bangsa.
Di tangan-Mu sejarah dunia berjalan, dan tidak ada satu pun bangsa yang berada di luar kedaulatan-Mu.
Kami bersyukur karena melalui sejarah Israel Engkau menyatakan diri-Mu kepada manusia dan menghadirkan Juruselamat bagi dunia dalam diri Yesus Kristus. Melalui karya keselamatan-Nya, Engkau membuka jalan bagi semua bangsa untuk mengenal kasih dan kebenaran-Mu.
Namun kami juga menyadari kelemahan hati manusia.
Kadang kami tergoda untuk meninggikan satu bangsa secara berlebihan, seolah-olah mereka lebih layak dari bangsa lain. Di lain waktu, kami juga dapat jatuh ke dalam sikap kebencian, prasangka, atau penghakiman yang tidak benar.
Ampunilah kami, Tuhan.
Ajarlah kami melihat sejarah dengan mata iman.
Tolonglah kami memahami bahwa rencana-Mu selalu lebih besar daripada kepentingan satu bangsa, satu kelompok, atau satu generasi.
Jauhkan hati kami dari pemujaan manusia atau bangsa mana pun.
Tetapi juga jauhkan kami dari kebencian, permusuhan, dan prasangka terhadap siapa pun.
Ajarlah kami menghormati semua manusia sebagai ciptaan-Mu, dan menilai segala sesuatu dengan hikmat, keadilan, dan kasih.
Kiranya hati kami tetap tertuju kepada Kristus saja sebagai pusat iman kami, sebab hanya Dia yang adalah Tuhan dan Juruselamat bagi seluruh dunia.
Bimbinglah kami untuk hidup dalam kerendahan hati, dalam kebenaran, dan dalam kasih kepada semua bangsa, sampai kehendak-Mu digenapi di bumi seperti di surga.
Di dalam nama Tuhan kami berdoa.
Amin.
“Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu.” Yesaya 55:8–9

Ketika perang atau konflik besar terjadi di dunia, banyak orang segera bertanya: siapa yang akan menang? Pertanyaan ini wajar, karena manusia selalu ingin mengetahui akhir dari sebuah peristiwa. Dalam konflik di Timur Tengah saat ini, misalnya, ada orang yang berkata bahwa pihak tertentu pasti menang karena mereka “bersama Tuhan”.
Namun benarkah manusia dapat memastikan hal itu?
Dalam sejarah, keyakinan seperti ini sering muncul. Banyak bangsa percaya bahwa kemenangan mereka adalah bukti bahwa Tuhan berada di pihak mereka. Tetapi Alkitab sendiri menunjukkan bahwa kenyataan tidak selalu demikian.
Bangsa Israel dalam Perjanjian Lama adalah umat pilihan Tuhan. Namun mereka tidak selalu menang dalam peperangan. Kadang mereka justru mengalami kekalahan yang pahit. Kota Yerusalem pernah dihancurkan, dan bangsa itu pernah dibuang ke Babel. Semua itu terjadi bukan karena Tuhan kehilangan kuasa, melainkan karena rencana-Nya jauh lebih besar daripada sekadar kemenangan militer.
Alkitab berulang kali mengingatkan bahwa pikiran manusia sangat terbatas dibandingkan dengan kehendak Tuhan.
Ayat di atas mengajarkan satu sikap penting dalam iman: kerendahan hati. Kita boleh memiliki pandangan, analisis, atau harapan, tetapi kita tidak pernah benar-benar mengetahui seluruh rencana Tuhan.
Bahkan dalam kitab Daniel dikatakan bahwa Tuhanlah yang mengubah waktu dan masa, Ia yang memecat raja dan mengangkat raja. Artinya, sejarah dunia ada di bawah kedaulatan Tuhan.
Kerajaan datang dan pergi, bangsa-bangsa bangkit dan jatuh, tetapi Tuhan tetap memegang kendali.
Karena itu, terlalu berani jika manusia dengan mudah berkata bahwa Tuhan pasti memihak satu pihak tertentu dalam sebuah konflik politik atau militer.
Lebih bijaksana jika kita mengakui bahwa rencana Tuhan sering kali melampaui perhitungan manusia. Kemenangan yang tampak besar hari ini bisa saja hanya sementara dalam perjalanan sejarah yang panjang.
Sejarah dunia memberikan banyak contoh. Kerajaan besar seperti Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi pernah terlihat begitu kuat dan tak tergoyahkan. Namun akhirnya semuanya berlalu. Tidak ada kekuatan dunia yang bertahan selamanya.
Hal ini mengingatkan kita bahwa tujuan utama rencana Tuhan bukanlah kemenangan suatu negara dalam jangka pendek. Rencana Tuhan jauh lebih besar daripada itu. Ia bekerja melalui sejarah untuk membawa manusia kepada pengenalan akan Dia, dan pada akhirnya kepada penggenapan kerajaan-Nya yang kekal.
Bagi orang percaya, harapan terbesar bukanlah kemenangan militer sebuah bangsa, melainkan kemenangan kebenaran Tuhan pada akhirnya.
Karena itu, ketika melihat keadaan geopolitik dan konflik dunia, mungkin sikap yang paling bijak adalah tetap berdoa, menjaga kerendahan hati, dan mengingat bahwa Tuhan tetap berdaulat atas sejarah. Kita tidak selalu memahami jalan-Nya, tetapi kita percaya bahwa Dia memegang masa depan.
Doa Penutup
Tuhan yang berdaulat atas sejarah,
Engkau memegang bangsa-bangsa dan masa depan dunia di tangan-Mu.
Sering kali kami mencoba menilai dan menebak rencana-Mu dengan pikiran kami yang terbatas. Ampuni kami jika kami terlalu cepat mengklaim mengetahui kehendak-Mu.
Ajarlah kami memiliki hati yang rendah dan percaya kepada kedaulatan-Mu.
Di tengah konflik dan peperangan di dunia ini, kami berdoa agar Engkau memberikan damai, menahan kejahatan, dan menolong mereka yang menderita.
Tolong kami untuk tidak menaruh harapan pada kekuatan manusia, tetapi pada kerajaan-Mu yang kekal.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.
“Orang bebal berkata dalam hatinya: ‘Tidak ada Allah!’ Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik.” Mazmur 53:2
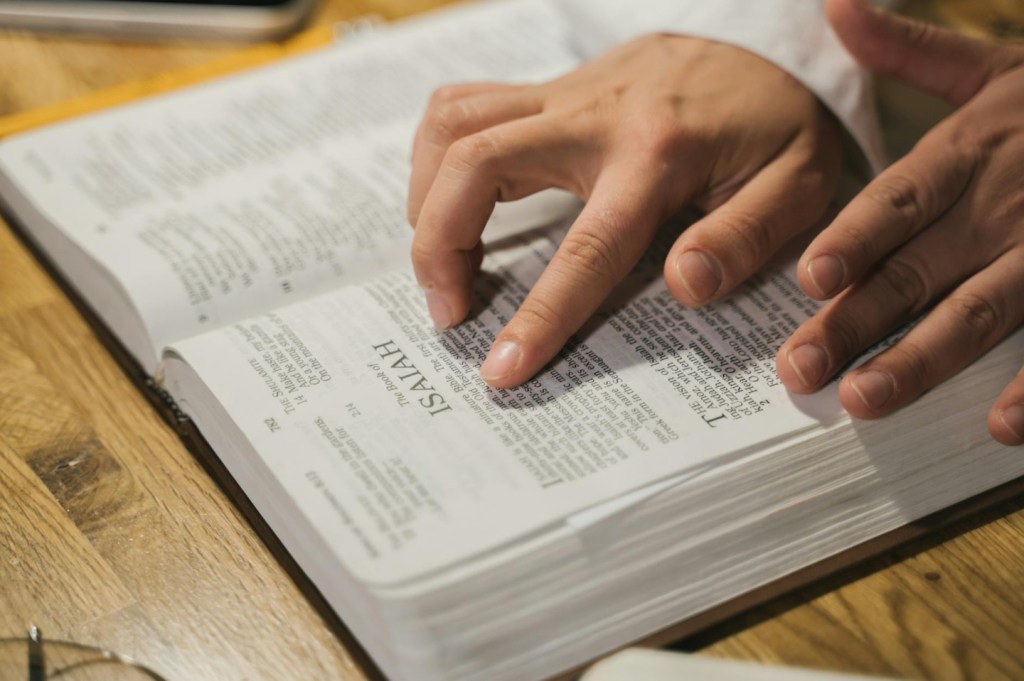
Di zaman modern ini, kebebasan sering dianggap sebagai nilai tertinggi. Banyak orang merasa bahwa manusia baru benar-benar bebas jika tidak ada otoritas yang lebih tinggi yang mengatur hidupnya. Bagi mereka, gagasan tentang Allah terasa seperti pembatas. Jika Allah tidak ada, maka manusia merasa bebas menentukan sendiri apa yang benar dan salah. Dan semua berjalan hanya menurut hukum menabur dan menuai.
Namun Mazmur 53 memberikan perspektif yang sangat berbeda. Pemazmur berkata bahwa orang yang berkata dalam hatinya, “Tidak ada Allah,” adalah orang bebal. Menariknya, kata ini tidak terutama menunjuk pada kurangnya kecerdasan. Alkitab tidak sedang mengatakan bahwa orang tersebut tidak pandai. Sebaliknya, kebebalan ini bersifat moral dan rohani.
Dengan kata lain, masalahnya bukan pada kemampuan berpikir, tetapi pada sikap hati.
Mazmur itu secara khusus mengatakan bahwa orang bebal berkata “dalam hatinya.” Artinya, ini bukan sekadar pernyataan intelektual. Ini adalah keputusan batin. Seseorang bisa saja memiliki berbagai argumen filosofis tentang keberadaan Allah, tetapi pemazmur menyoroti sesuatu yang lebih dalam: keinginan manusia untuk hidup tanpa pertanggungjawaban kepada Penciptanya, tapi kepada dirinya sendiri.
Di sinilah letak perbedaan antara bebas dan bebal.
Manusia memang diciptakan dengan kebebasan tertentu. Allah memberi kita akal budi, kehendak, dan kemampuan memilih. Tetapi kebebasan itu tidak pernah dimaksudkan sebagai kebebasan tanpa arah.
Kebebasan sejati selalu berjalan bersama kebenaran Ilahi.
Jika seseorang menolak Allah demi kebebasan mutlak, ia sebenarnya sedang menukar kebebasan dengan sesuatu yang jauh lebih buruk. Tanpa Allah, standar moral menjadi kabur. Apa yang benar dan salah akhirnya ditentukan oleh kepentingan pribadi, kekuasaan, atau selera zaman.
Mazmur 53 menggambarkan akibatnya dengan kata-kata yang sangat keras: manusia menjadi korup, melakukan hal-hal yang menjijikkan, dan tidak ada yang berbuat baik. Tetapi, mereka tidak sadar bahwa mereka adalah manusia berdosa karena tidak percaya adanya Tuhan yang mahasuci.
Ini bukan sekadar kritik terhadap kelompok tertentu. Mazmur ini sebenarnya membuka kenyataan yang lebih luas tentang kondisi manusia. Ketika manusia memutuskan untuk hidup tanpa Allah, kerusakan moral tidak bisa dihindari atau disadari.
Sejarah manusia penuh dengan contoh. Ideologi yang menyingkirkan Allah sering kali menjanjikan kebebasan besar bagi manusia. Namun pada akhirnya, yang muncul justru penindasan, kekerasan, dan hilangnya nilai kehidupan manusia.
Mengapa demikian?
Karena ketika Allah disingkirkan, manusia dengan mudah menempatkan dirinya sendiri sebagai pusat segala sesuatu. Dan ketika manusia menjadi pusat, ego, kekuasaan, dan keinginan pribadi perlahan-lahan mengambil alih. Itu bisa terjadi dalam keluarga, negara dan juga gereja.
Namun kabar baik dari Alkitab adalah bahwa Allah tidak meninggalkan manusia dalam kebebalan itu. Sepanjang sejarah keselamatan, Allah terus memanggil setiap manusia untuk kembali kepada-Nya. Ia membuka mata hati manusia untuk melihat bahwa hidup yang benar bukanlah hidup tanpa Allah, tetapi hidup bersama Dia.
Justru di dalam pengenalan akan Allah, manusia menemukan kebebasan yang sejati.
Kebebasan sejati bukanlah kemampuan untuk melakukan apa yang diingini asal tidak mengganggu orang lain.
Pikiran manusia tidak bisa menjamin bahwa mereka bisa memilih apa yang baik.
Kebebasan sejati adalah kemampuan untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan dan tujuan kita diciptakan. Ini memerlukan hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Seperti ikan yang bebas di dalam air, manusia paling bebas ketika ia hidup dalam hubungan dengan Penciptanya. Tanpa Allah, kebebasan berubah menjadi kebebalan. Tetapi bersama Allah, kebebasan berubah menjadi kehidupan yang penuh makna.
Mazmur 53 mengingatkan kita untuk memeriksa hati kita sendiri. Apakah kita hidup seolah-olah Allah tidak ada? Ataukah kita hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah kita berada di hadapan-Nya?
Hikmat rohani dimulai bukan dari kecerdasan manusia, tetapi dari hati yang mau mengakui Tuhan. Di situlah kebebasan yang sejati ditemukan.
Doa Penutup
Tuhan yang Mahakudus, kami mengakui bahwa sering kali hati kami ingin hidup tanpa batasan, tanpa pertanggungjawaban kepada-Mu. Kami mudah tergoda untuk mengandalkan pikiran kami sendiri dan melupakan bahwa Engkaulah Pencipta dan Hakim atas hidup kami.
Ampuni kami jika dalam sikap, keputusan, atau cara hidup kami, kami seakan-akan berkata dalam hati bahwa Engkau tidak ada. Bukalah mata hati kami supaya kami melihat bahwa kebebasan sejati hanya ada di dalam Engkau.
Ajarlah kami untuk hidup dengan takut akan Tuhan, bukan sebagai beban, tetapi sebagai jalan menuju kehidupan yang benar dan penuh makna.
Bentuklah hati kami agar kami tidak menjadi bebal, tetapi menjadi bijaksana di hadapan-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.
“Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. “Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 1 Korintus 10:23

Suatu hari seseorang bertanya dengan tulus, “Apakah orang Kristen patut menonton festival budaya yang di dalamnya ada unsur ritual dan kepercayaan kepada roh?” Pertanyaan itu bukan lahir dari rasa ingin tahu biasa, tetapi dari hati yang ingin setia. Bukan karena takut kepada roh-roh, melainkan karena takut melanggar perintah Tuhan untuk menjauhi berhala.
Kita hidup di dunia yang majemuk. Ada banyak perayaan budaya, termasuk festival seperti Cap Go Meh Singkawang, yang menampilkan kekayaan tradisi, seni, dan juga unsur spiritual yang bukan berasal dari iman Kristen. Di satu sisi, itu adalah fenomena budaya yang menarik. Di sisi lain, ada ritual yang jelas berakar pada kepercayaan tertentu.
Di Sydney, setiap tahun ada parade kaum LGBTIQ+ yang dinamakan Mardi Gras. Ribuan penonton datang dari berbagai tempat, termasuk turis dari luar negeri. Mereka merayakan kebebasan identitas golongan mereka dengan parade dansa dansi dengan pakaian minim. Tetapi banyak juga keluarga yang menonton bersama anak-anak mereka. Di satu sisi, parade ini merayakan kebebasan dan hak asasi manusia. Di pihak lain, tontonan ini dipandang sebagai hal yang melampaui standar moral sebagian orang.
Lalu bagaimana sikap orang percaya?
Sering kali kita terjebak pada dua ekstrem. Yang pertama adalah ketakutan: seolah-olah dengan menonton saja kita sudah membuka pintu bagi kuasa gelap. Yang kedua adalah kecerobohan: merasa semua boleh karena kita hidup dalam anugerah. Padahal Alkitab memberi jalan yang lebih dewasa.
Paulus tidak berkata bahwa semua yang “boleh” otomatis baik untuk jiwa kita. Ia menambahkan ukuran yang lebih tinggi: berguna dan membangun.
Ukuran orang percaya bukan sekadar benar atau salah, tetapi apakah sesuatu itu memperkuat kasih kita kepada Kristus.
Menonton bukanlah penyembahan. Mengamati bukanlah partisipasi. Namun hati kita tetap bisa terpengaruh oleh apa yang kita nikmati dan kagumi. Jika sebuah tontonan menimbulkan kekaguman rohani terhadap kuasa selain Tuhan, atau mengaburkan keunikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan, maka itu tidak lagi netral bagi jiwa.
Di sisi lain, tidak semua yang mengandung unsur budaya non-Kristen otomatis menjadi dosa untuk dilihat.
Yang menentukan bukan hanya objeknya, tetapi sikap hati dan dampaknya.
Paulus dalam 1 Korintus 10 bahkan rela membatasi kebebasannya demi saudara yang imannya lebih lemah. Artinya, kasih lebih tinggi dari sekadar hak pribadi.
Ada orang yang semakin dewasa rohani menjadi semakin sederhana dalam pilihan hidupnya. Ada juga yang tidak semakin sederhana, tetapi semakin selektif. Selektif berarti menimbang dengan sadar: apakah ini layak untuk mata dan hati. Dosa bisa datang dari mata dan kemudian turun ke hati. Karena itu kita harus sangat berhati-hati. Apakah ini membantu saya memuliakan Tuhan? Apakah ini akan membangun orang lain atau justru membingungkan mereka?
“Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu dari pada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua.” Matius 18:9
Tidak semua yang netral perlu dikonsumsi. Tidak semua yang tersedia perlu dinikmati.
Waktu dan perhatian kita adalah bagian dari ibadah kita. Apa yang sering kita lihat dan nikmati perlahan membentuk selera dan arah hati.
Menjauhi sesuatu bukan selalu tanda ketakutan. Kadang itu tanda prioritas. Kadang itu penting untuk mengarahkan anak cucu kita ke arah yang lebih penting. Bukan karena kita menganggap roh-roh itu hebat, tetapi karena kita tahu Kristus jauh lebih mulia sehingga kita tidak mau mengisi hati dengan hal yang tidak menolong kita mengasihi-Nya lebih dalam.
Akhirnya, hidup yang memuliakan Tuhan bukan hidup yang steril dari dunia, tetapi hidup yang tahu mana yang bernilai kekal dan mana yang hanya lewat sesaat. Bukan hidup dalam kecemasan, tetapi hidup dalam kebijaksanaan. Karena memang benar: tidak semua berguna. Dan hati yang rindu memuliakan Tuhan akan belajar berkata dengan tenang, “Saya memilih yang membangun.”
Doa Penutup
Tuhan yang kudus dan penuh kasih, ajarilah kami hidup dengan bijaksana di tengah dunia yang beragam ini.
Berikan kami hati yang peka, bukan hati yang takut, dan kebebasan yang dewasa, bukan kebebasan yang ceroboh.
Tolong kami menilai segala sesuatu dengan terang firman-Mu.
Jika sesuatu tidak berguna bagi jiwa kami, berikan keberanian untuk meninggalkannya.
Jika sesuatu berpotensi menjadi batu sandungan, berikan kasih untuk mengutamakan sesama.
Jagalah hati kami supaya tetap tertuju kepada Kristus, sehingga dalam apa pun yang kami lakukan — melihat, mendengar, atau memilih —nama-Mu yang dimuliakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.